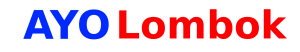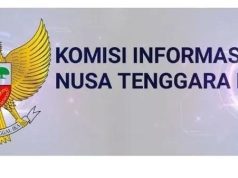Oleh : Lalu Wisnu Pradipta
Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah gencar mempromosikan diri sebagai daerah yang “mendunia”—modern, bersih, dan siap bersaing dalam berbagai sektor pembangunan. Lombok Timur pun ikut bergerak melalui gagasan Lotim Smart, sebuah konsep daerah cerdas yang menempatkan tata kelola, teknologi, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama.
Namun ada satu ironi besar yang tidak bisa kita tutup mata: sampah. Di tengah narasi kemajuan, masalah sampah di Lombok Timur justru seperti jalan di tempat. Bahkan bisa dibilang semakin membesar.
Paradigma Salah: Semakin Banyak Sampah Terangkut, Semakin Baik?
Selama ini ukuran keberhasilan penanganan sampah seakan hanya dilihat dari banyaknya armada pengangkut sampah di desa, atau semakin banyak volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sayangnya, indikator ini justru menggambarkan betapa kita masih terjebak dalam pola pikir lama.
Jika 50% lebih sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah organik, bukankah itu menunjukkan kegagalan?
Karena sampah organik adalah jenis sampah yang paling mudah diselesaikan di rumah tangga,tanpa peralatan mahal, tanpa teknologi rumit.
Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi masalah pemahaman: pengurangan sampah seharusnya dimulai dari rumah, bukan dari bak sampah desa.
Desa Punya Lahan Yang Luas, Tapi Mengapa Sampah Organik Tetap Dibuang ke TPA?
Di desa-desa Lombok Timur, hampir setiap rumah memiliki pekarangan atau tanah terbuka. Namun realitasnya, sampah dapur tetap dimasukkan ke kantong plastik, dikumpulkan, lalu menunggu armada datang mengangkutnya ke TPA.
Fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi dasar dalam pengelolaan sampah belum pernah sungguh-sungguh dikerjakan.
Padahal inovasi paling sederhana adalah mengolah sampah di tempatnya, bukan memindahkannya.
Ketika Armada Pengangkut Justru “Mematikan” Kepedulian Masyarakat
Inilah masalah terbesar: mentalitas.
Ketika pemerintah menyediakan armada untuk mengambil sampah, masyarakat menjadi ketergantungan. Mereka berhenti bertanggung jawab atas sampahnya sendiri.
Logikanya menjadi sederhana: “Untuk apa repot mengolah sampah organik? Toh nanti diangkut.” Masyarakat juga malas mengolah sampah dapur karena merasa sudah membayar iuran sampah sehingga bak sampah adalah solusi, Bukan inovasi.
Akibatnya, konsep antisipasi hilang.
Kesadaran hilang.
Gotong royong hilang.
Analogi mudahnya, masyarakat menjadi seperti warga yang tidak lagi takut banjir karena pemerintah sudah menyiapkan sampan untuk evakuasi. Akhirnya mereka berhenti melakukan pencegahan, dan hanya menunggu ditolong ketika bencana datang.
Demikian pula urusan sampah: ketika fasilitas datang, kepedulian pergi.
Lotim Smart Akan Tetap Cuma Slogan
Jika pola pikir ini dibiarkan, Lombok Timur akan sulit menyandang predikat daerah cerdas.
Bagaimana mungkin daerah “smart” jika masalah paling mendasar, yaitu sampah, tidak ditangani dari hulu?
• TPA terus menumpuk
• Desa menghasilkan sampah lebih banyak
• Sampah organik tetap bercampur dengan plastik
• Masyarakat tidak mau mengolah sampahnya sendiri
• Dan pemerintah sibuk menambah armada alih-alih menekan sumber sampah
Di mana letak “smart”-nya jika sistem kita hanya memindahkan sampah, bukan menguranginya?
*Saatnya Mengubah Arah*
Jika NTB ingin benar-benar mendunia dan Lombok Timur ingin betul-betul cerdas, pengelolaan sampah harus kembali ke prinsip dasar:
1. Sampah organik harus selesai di rumah tangga.
2. Pengangkutan bukan prioritas, tetapi opsi terakhir.
3. Inovasi sederhana harus diperkuat, bukan sekadar infrastruktur.
4. Edukasi dan kesadaran lingkungan harus dihidupkan kembali.
5. Desa harus menjadi lokomotif perubahan, bukan sekadar terminal sampah.
Lotim Smart bukan soal aplikasi teknologi.
Ia tentang bagaimana masyarakat berpikir, bersikap, dan bertanggung jawab pada lingkungan.
Jika kita ingin NTB mendunia, maka kita harus mulai dari yang paling dasar:
mengurus sampah kita sendiri.
Sebelum berbicara tentang smart city, mari kita belajar menjadi smart community.
Karena kemajuan bukan dimulai dari spanduk dan slogan, tetapi dari kesadaran masyarakat untuk menjaga bumi tempatnya berpijak.
(NB : Tulisan ini saya buat setelah menghadiri acara Konsultasi publik Penyusunan RAD-TPB/SDGs tahun 2025-2029)